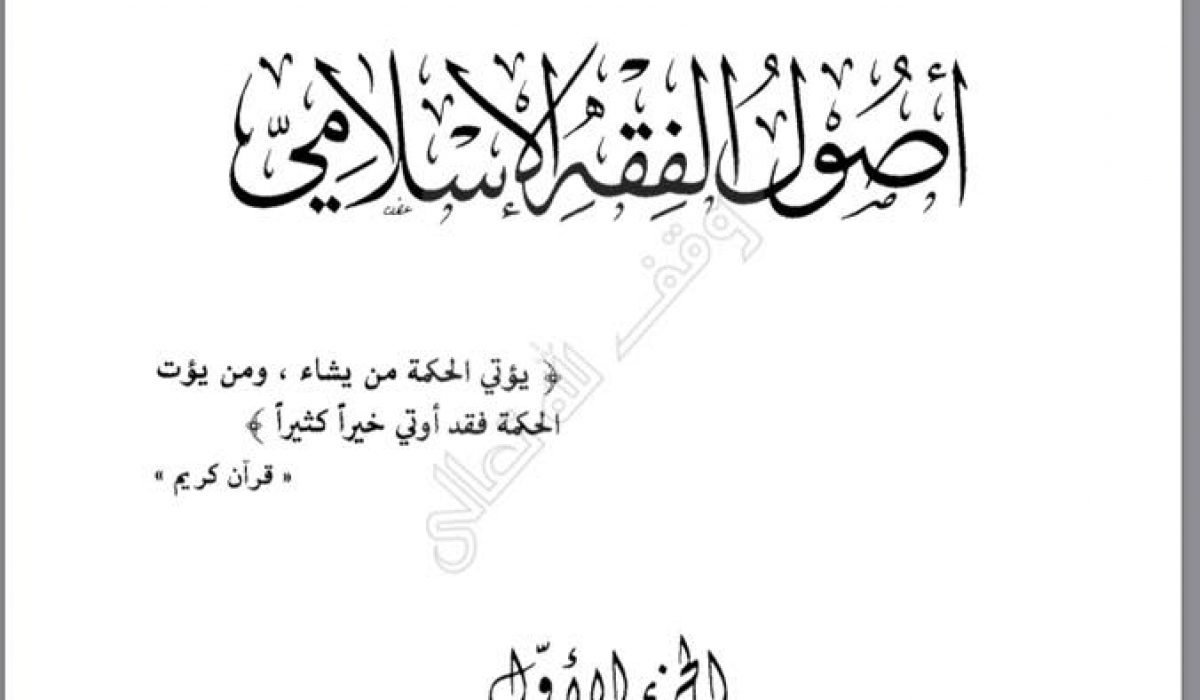Kebenaran ilmiah harus ditegakkan. Jangan mudah mengklaim terjadinya ijma’, jika memang masih terdapat perselisihan atau perbedaan pandangan diantara ulama. Kita harus fair dan jujur. Kalau ada perbedaan pendapat, sebutkan, jangan disembunyikan. Kalaupun kita tidak setuju dengan pendapat yang berbeda itu, tetaplah keberadaan pendapat itu harus kita hargai dan karenanya tidak bisa kita mengklaim telah terjadi Ijma’ (konsensus).
Mari kita ngaji Bab Ijma’ seperti terdapat dalam kitab Ushul al-Fiqh al-Islamiy karya Syekh Wahbah az-Zuhaili (jilid 1, halaman 486-491).
Syekh Wahbah az-Zuhaili mengutip klaim Abu Ishaq yg mengatakan telah terjadi ijma’ lebih dari 20 ribu kasus hukum. Benarkah klaim ini? Apakah ijma’ yang dimaksud ini merupakan ijma sebagai sumber hukum ketiga, yang bersifat qat’i dan sesiapa penentangnya dianggap keluar dari Islam?
Nah, Syekh Wahbah mengajak kita utk berhati-hati dlm memverifikasi klaim ijma’ ini. Banyak ternyata yang diklaim itu bukan ijma’ (konsesus semua ulama) tapi hanya ittifaq (kesepakatan) diantara para imam mazhab, atau satu mazhab, atau karena tidak diketahui ada yang menyelisihi pendapat itu.
Pangkal perdebatan ini dikarenakan mengenai definisi ijma’ itu sendiri yang belum disepakati. Syekh Wahbah menyodorkan 2 definisi, satu dari Imam al-Ghazali, dan satu lagi dari jumhur ulama. Imam al-Ghazali berpendapat bahwa ijma’ itu kesepakatan umat Muhammad secara khusus tentang masalah agama.
Sementara itu jumhur ulama berpendapat: ijma’ itu kesepakatan mujtahid umat Muhammad pasca wafatnya beliau di suatu masa tentang hukum syar’i.
Kedua definisi yang berbeda ini menimbulkan perbedaan konsekuensi dalam aplikasi ijma’ sebagai sumber hukum ketiga dalam Islam.
Dalam definisi Imam al-Ghazali, ijma’ melibatkan semua umat, tidak hanya para mujtahid. Ini sesuai bunyi hadits Nabi bahwa umatku tidak akan bersepakat atas kesalahan atau kesesatan. Dan juga tidak disyaratkan kesepakatan itu terjadi hanya di masa setelah Nabi.
Syekh Wahbah memandang definisi ijma’ menurut Imam al-Ghazali itu problematik. Misalnya pada masa hidup Nabi kita tidak butuh ijma’ karena Nabi tempat bertanya dan menjadi sumber hukum. Jadi definsi jumhur lebih kuat dan pas.
Selesai kutipan dari kitab Syekh Wahbah az-Zuhaili. Masih banyak bahasan beliau yang sangat menarik, namun kita beralih ke kitab lain agar semakin kaya referensi kita.
Dawud Zhahiri dan Ibn Hibban berpendapat bahwa ijma’ hanyalah berlaku untuk sahabat Nabi, tidak untuk yang lain. Imam Ahmad –dalam satu riwayat– mengatakan bahwa ijma’ itu adalah kesepakatan khulafa al-rasyidin saja. Imam Malik malah merujuk pada ijma’ penduduk madinah.
Ulama lain merujuk pada ijma’ ahlul haramain (penduduk Mekkah dan Madinah). Sedangkan ulama yang lain menganggap ijma’ adalah kesepakatan penduduk Basrah dan Kufah saja; ada yang bilang kufah saja, bahkan ada juga yang bilang bahwa kesepakatan penduduk Basrah saja sudah cukup dipandang sebagai ijma’ [Lihat Ibn Hazm, “al-Ihkam fi Usul al-Ahkam,” juz 4, h. 128; al-Amidi, “al-Ihkam fi Usul al-Ahkam,” juz 1, h. 286, 380-381, dan 404-405; al-Syaukani, “Irsyad al-Fuhul,” h. 70, dan 79-80.]
Para ulama ada yang menyusun kriteria terwujudnya ijma’, yaitu ijma’ tersebut diikuti oleh mereka yang memenuhi persyaratan berijtihad, kesepakatan itu muncul dari para mujtahid yang bersifat adil dan para mujtahid itu berusaha menghindarkan diri dari ucapan atau perbuatan bid’ah. Ada pula yang menambah syarat lain yaitu yang dimaksud dengan mujtahid adalah sahabat Nabi saja, ada lagi yang menganggap mujtahid yang dimaksud hanyalah keluarga Nabi saja; sementara itu ada yang berpendapat –seperti telah disinggung sebelumnya– mujtahid itu hanya ulama Madinah saja.
Ada pula yang berpendapat bahwa hukum yang disepakati itu tidak ada yang membantahnya sampai wafatnya seluruh mujtahid yang telah menyepakatinya serta tidak terdapat hukum ijma’ sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang sama. Ada pula yang berpendapat ijma’ yang terbaru bisa menghapus ijma’ yang lalu, dengan berbagai persyaratan yang ketat. Pendek kata, seru deh perdebatan para ulama.
Sekadar menyebut contoh yang kontroversial, kitab al-Mughni (2/243) dan Nail al-Awthar (3/223) menyebutkan telah terjadi ijma’ dalam hal fardhu ‘ain-nya sholat jum’at. Padahal Ibn Rusyd dalam Bidayatul Mujtahid (1/126) menyebutkan itu hanya pendapat jumhur ulama; bukan ijma’. Kitab fiqh yang terakhir ini menyebutkan adanya sekelompok ulama yang berpendapat bahwa sholat jum’at itu fardhu kifayah; bahkan ada satu riwayat syadz dari Imam Malik mengatakan sholat jum’at itu sunnah.
Bukanlah menjadi tujuan tulisan ini membahas soal kewajiban sholat jum’at. Namun dari contoh soal sholat jum’at ini kita bisa menangkap adanya ketidaksepakatan dalam menentukan apakah satu masalah sudah di-ijma’-kan atau belum.
Dengan kita luaskan bacaan kita (tidak hanya merujuk pada satu atau dua kitab fiqh), boleh jadi masalah-masalah yang selama ini kita anggap merupakan ijma’ ternyata belum merupakan ijma’ atau sebuah kesepakatan yang mengikat.
Sejarah juga mencatat bahwa kegagalan mencapai kesepakatan tersebut kemudian melahirkan berbagai bentuk “kompromi”. Misalnya, andaikata semua ulama telah sepakat pada satu hal, maka ini dipandang cukup mewakili kesepakatan ummat Islam secara total. Hal ini kemudian bergeser lagi karena ternyata cukup sulit menyatukan pendapat para ulama itu. Kebenaran bukan lagi dilihat berdasarkan kesepakatan total ummat Islam atau kesepakatan ulama, melainkan suara mayoritas di antara para ulama.
Jikalau kitab-kitab fiqh sudah menyebut bahwa pendapat A dipegang oleh jumhur (mayoritas) ulama, jarang para santri atau ulama berani membantah atau, setidak-tidaknya, bersikap kritis. Mayoritas telah memegang otoritas kebenaran. Kebenaran bukan lagi ditentukan oleh kekuatan dalil dan logika, namun mengikuti jumlah pemegang pendapat tersebut.
Berbeda dengan istilah Ijma’, lahir istilah baru untuk menggambarkan pergeseran ini, yaitu ittifaq. Sehinga kalau ditemukan kalimat bahwa para ulama sudah ittifaq untuk berpendapat A, boleh jadi yang dimaksud sebenarnya adalah hanya kesepakatan para ulama dari mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali), padahal jumlah mazhab dalam Islam konon pernah mencapai bilangan lima ratus.
Masalahnya ternyata tidak mudah menentukan apakah satu pendapat itu didukung oleh mayoritas atau minoritas. Boleh jadi pendapat A didukung oleh mayoritas pada suatu masa di suatu tempat tertentu. Namun di masa lain atau di tempat lain, boleh jadi yang mayoritas adalah B.
Problem kedua, Bagaimana cara menghitung “kursi” mayoritas tersebut? Karena belum pernah dihitung lewat pemilu, maka kitab-kitab fiqh diduga kuat hanya melakukan perhitungan secara umum saja. Boleh jadi, problem ini menimbulkan saling klaim di antara mereka.
Yang penting, sebagai santri dan pelajar, selain kita harus jujur untuk menampilkan pendapat yang berbeda, kita juga harus berlapang dada terhadap perbedaan pendapat. Keragaman itu indah. Jangan memaksa semua orang harus seragam pada masalah-masalah yang para ulama masih berbeda pandangan. Jangan mudah mengklaim terjadinya ijma’.
Umat Islam harus terus diajarkan bahwa perbedaan pendapat itu hal biasa. Gak usah marah-marah apalagi sampai hilang adab dengan mengeluarkan kata cacian. Hanya dengan cara seperti ini kita akan bertambah dewasa dan tidak gampang menyalahkan pihak lain, apalagi sampai mengintimidasi mereka yang berpegang pada pendapat yang berbeda.
Ingat yah: berbeda itu hal biasa saja. Gitu aja kok repot
Tabik,
Nadirsyah Hosen
Ps.
Skrinsut dari kitab Ushul al-Fiqh al-Islamiy karya Syekh Wahbah az-Zuhaili pada pokok bahasan ini saya sertakan untuk mereka yang hendak menelaah lebih lanjut.